Pekerjaan yang paling menyedihkan adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kiranya itulah yang terjadi jika kita menceritakan tentang kehancuran hutan Indonesia. Sesuatu yang sangat jelas terjadi di depan mata. Bahkan, sebagian dari kita mungkin terlibat dalam kehancuran itu, baik sebagai penyebab maupun sebagai penerima dampak. Sederhananya, telah terjadi pergeseran nalar yang menyebabkan hutan memiliki banyak makna.
Hutan yang pada hakikatnya adalah modal alam, tempat dimana berbagai komponen ekosistem tumbuh dan berkembang, justru dijadikan sebagai komoditas sehingga dimanfaatkan secara terus menerus, tanpa ada niat untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya. Jika ditanya penyebab terjadinya permasalahan hutan di Indonesia, mungkin mayoritas dari kita akan langsung mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi dan dominannya sifat kerakusan. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Karena yang berada di balik permasalahan tersebut tidak ubahnya seperti jaring yang kait mengait dan tak berujung berpangkal. Sungguh dinamis.
Tentu akan sangat mudah menuding pihak mana yang harus bertanggung jawab atas permasalahan ini – siapa yang menanam, dia yang memanen – itulah yang kita lakukan selama ini. Pemerintah dan korporasi kerap dituding sebagai aktor penyebab kehancuran.Suatu hal yang cenderung menyederhanakan masalah. Karena proses ini sesungguhnya melibatkan banyak manusia dengan beragam latar belakang dan kepentingan. Intelektual adalah salah satu pihak yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia, terutama berkaitan dengan perkembangan dan implementasi ilmu pengetahuan. Para intelektual ini termanifestasikan dalam berbagai profesi, baik akademis maupun non-akademis, baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan, dan lain sebagainya.
Sebagai sesuatu yang dinamis, generasi intelektual terus berganti, mengalir seiring kemajuan zaman. Sudah pasti permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks dan dinamis. Inilah tantangan terbesar bagi kita, intelektual muda. Intelektual muda tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan perubahan. Peter Brian Medawar, pakar fisiologi kedokteran dari University of London yang juga pemenang hadiah Nobel 1960, bahkan menulis buku khusus yang berjudul Advice to a Young Scientist pada tahun 1979. Buku ini bertujuan untuk memperkuat jati diri para intelektual muda dalam menetapkan pilihan jalan hidup, khususnya bagi yang berniat menjadi ilmuwan. Sindrom yang sering dihadapi oleh intelektual muda adalah idealisme dan ketergesaan. Dua hal yang saling bertentangan dan sama bahayanya. Lalu, bagaimanakah seharusnya intelektual muda bersikap?
Ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui fungsi intelektual. Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia, membedakan intelektual menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) intelektual tradisional, yang menjadi penyebar ide dan mediator; (2) intelektual organik, yang memberikan refleksi atas keadaan, tetapi biasanya terbatas hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, dalam hal ini adalah kalangan profesional; (3) intelektual kritis, adalah kelompok yang mampu melepaskan diri dari hegemoni penguasaan elite penguasa yang sedang memerintah; (4)intelektual universal, yang selalu memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya dalam rangka memanusiakan manusia agar harkat dan martabatnya dihormati.
Pengelompokan yang diutarakan oleh Antonio Gramsci sudah cukup jelas bagi kita untuk sekadar mengidentifikasi diri – kita intelektual yang mana? – Suatu pilihan yang memuat berbagai konsekuensi. Dalam ranah yang lebih khusus untuk melihat hubungan antara intelektual dan isu kehutanan. Witmer and Birner (2005) mendapati tiga diskursus dalam dua studi kasus di Indonesia dan Thailand, yaitu konservasi, ekopopulis dan developmentalis. Ketiga diskursus ini memiliki perbedaan dalam aspek prioritas/misi, posisi, dan relasi keilmuan.
Diskursus pertama berargumentasi bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi secara hukum yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan manusia. Tujuannya untuk mewujudkan keseimbangan ekologi sehingga akses terhadap kawasan konservasi harus ditutup dengan penjagaan yang sangat ketat. Penduduk yang mendiami kawasan itu pun harus dikeluarkan.
Diskursus kedua berargumentasi bahwa masyarakat sekitar kawasan konservasi adalah pemegang hak atas sumber daya alam. Mereka beserta nilai dan adat istiadatnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang harus dilindungi.
Diskursus ketiga beranggapan bahwa kerusakan sumberdaya alam disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan telah ‘memaksa’ mereka yang tinggal sekitar kawasan konservasi merambah dan mengambil manfaat dari kawasan itu demi kelangsungan hidupnya.
Satu hal yang selalu mengusik pikiran adalah, kita selalu menggembar-gemborkan netralitas,“menari” di antara “genderang” ekonomi dan lingkungan. Nyatanya, kita tidak pernah benar-benar menjadi netral. Kepentingan dan nilai-nilai yang kita anut terhadap suatu permasalahan adalah suatu keniscayaan. Bahkan, ilmu pengetahuan pun tidak bebas dari nilai dan kepentingan. Hal ini pula yang mempengaruhi nalar dan tindakan kita. Ketiga diskursus yang dikemukakan oleh Witmer and Birner (2005) diatas semakin menegaskan mengenai kepentingan ini.
Dalam tataran teknis, posisi intelektual terhadap suatu permasalahan memang selalu memunculkan perdebatan dan ironi. Perguruan tinggi, tempat dimana intelektual terdidik berproses, pun tidak luput dari ironi. Beberapa waktu yang lalu, ratusan warga Kendeng, Pati, Jawa Tengah melakukan demonstrasi terhadap UGM. Karena AMDAL pembangunan sebuah Pabrik Semen dikeluarkan atas kajian akademisi UGM. Kejadian serupa terjadi di Pekanbaru,beberapa kelompok masyarakat mendatangi Universitas Riau, memprotes hasil penelitian yang dilakukan para akademisi di kampus itu yang memuluskan izin pembuangan limbah cair sebuah pabrik kelapa sawit, sehingga mengancam kelestarian sumber air masyarakat.
Tidak mengherankan jika kemudian perguruan tinggi sering absen dalam merespon kebijakan yang memuluskan kesenjangan. Sebab, mengutip tuduhan - In’amul Mushoffa & HarisSamsuddin - alih-alih menjalankan fungsi sebagai pembela kebenaran, perguruan tinggi hanya menjadi pemasok tenaga kerja industri.
Intelektual, dengan legitimasi keilmuan, mampu memberikan penekanan terhadap isu-isu yang berkembang. Sudah sangat lama kita disuguhkan oleh berbagai informasi kerusakan hutan yang itu-itu saja. Alangkah bijaksananya jika kita melihat dari sudut yang lain. Jangan-jangan kita adalah korban dari suatu konspirasi ilmu pengetahuan. Bjørn Lomborg, penulis buku The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, melemparkan tantangan secara luas kepada siapa saja yang meyakini bahwa keadaan lingkungan hidup saat ini terus bertambah buruk. Berbekal pengalaman yang panjang dengan berbagai LSM internasional, dia menyatakan bahwa organisasi-organisasi lingkungan secara selektif, dan bahkan mungkin menyesatkan, telah menggunakan bukti-bukti ilmiah untuk advokasi dan kampanye-kampanye nya. Pada bagian akhir bukunya, Bjørn Lomborg menyimpulkan bahwa terdapat lebih banyak alasan untuk optimis daripada bersikap pesimistis. Dia menekankan perlunya melakukan prioritas secara jernih dan dingin atas sumber daya - sumber daya yang tersedia untuk menangani masalah-masalah yang konkrit, bukan masalah yang dibayangkan (imagined problems).
Dalam kajian yang lebih spesifik, Ricky Avenzora pernah mengulas tentang "kemurnian suara" LSM lingkungan di Indonesia. Dia memberikan kritik terhadap pola sikap, tindakan, dan gerakan LSM yang terasa sangat ganjil ketika mereka sangat tendensius untuk menyudutkan semua pihak dan bahkan mencatut nama rakyat. LSM lingkungan dalam pandangan Ricky Avenzora, tidak luput dari pro dan kontra. Bagi mereka yang pro, tentunya berbagai gerakan LSM lingkungan selama ini adalah wujud dari sifat heroik yang patut dipuji. Namun bagi yang kontra, sikap-sikap LSM lingkungan yang selalu menyalahkan pihak yang mereka "bidik", tentunya akan melahirkan berbagai pertanyaan dan sangkalan yang perlu dicarikan jawabnya secara objektif.
Berbagai sisi negatif intelektual di atas kiranya jangan sampai mengurangi semangat kita untuk berjuang dan merubahnya menjadi sisi positif. Hidup memang selalu menyajikan pilihan, kita dituntut untuk cerdas dan cakap dalam bersikap. Bagi kita, intelektual muda, belumlah terlambat untuk menentukan pilihan dan respon terhadap isu permasalahan hutan.Tugas intelektual, menurut Edward Said, adalah menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan. Semoga kita bijak dalam “membaca” nasib hutan di tengah kerusakan yang semakin masif.
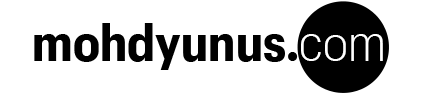



0 Komentar